KOTA RAHIMNYA PANCASILA
29 November 2017.
Pagi itu terbangun dengan rasa segar yang luar
biasa, mungkin hasil dari tidur panjang semalam setelah menikmati Soto Lamongan dan
empuknya kasur penginapan yang memeluk kelelahan saya.
Karena lapar dan penginapan tak
menyediakan sarapan, usai membersihkan diri saya cari keluar, para penghuni kos
lain tampak sedang bersiap untuk berangkat ke tempat kerjanya masing-masing.
Saya berkeliling sebentar di tengah kota Ende yang
mulai menggeliat, sebuah warung yang sedang ramai menarik perhatian, nasi
kuning istimewa, saya minta dibungkus saja.
Sambil sarapan, saya berbincang dengan pegawai
penginapan, ia sempat memberi sedikit peringatan bila nanti melewati Danau
Ranamese di Manggarai "tempatnya angker jika dilewati malam hari" katanya. Entah
mitos entah pengalaman, saya hanya tersenyum saja, tapi menyimpan informasi itu
di saku kecil perjalanan.
Mas Heru datang sesuai janji pagi itu, ia membawa
sebungkus nasi uduk untuk saya katanya, karena sudah makan, saya simpan saja
sebagai bekal nanti di jalan. Kami tinggalkan penginapan dan mulai menyusuri
kota di bawah matahari 25 derajat Celsius—udara yang ramah bagi pesepeda.
Perhentian pertama adalah titik nol kilometer di
seberang lapangan olahraga. Tempat ini menjadi spot foto wajib bagi para
petualang sepeda dan motor yang melintas di pulau ini, di depannya, sebuah
kantor pemerintah sedang ramai oleh kegiatan koordinasi kependidikan, detak
publik dan jejak sejarah bersisian di satu poros.
Tujuan selanjutnya menuju ke sebuah taman yang rindang—tempat
dulu Bung Karno sering nongkrong dan memikirkan nasib bangsanya di pengasingan,
ya di bawah pohon sukun itu. Dari pohon itu pula lahir gagasan besar bernama
Pancasila. lima daun, lima sila, sebuah renungan yang akhirnya menjadi fondasi
negeri.
Saya tak sabar untuk menuju situs berikutnya—rumah
pengasingannya. Di perjalanan beberapa orang tampak keheranan melihat saya
bersepeda dengan pannier besar dikawal petugas berseragam lengkap, mungkin
mereka mengira saya tokoh penting, saya hanya bisa menyapa dengan senyum tipis.
Rumah Bung Karno itu tampak sederhana namun
istimewa, bersih dan terawat. Ruang tamu, kamar tidur, dapur, masih dijaga
keasliannya, sementara sumur tua dengan kerekan dan embernya masih berdiri
dengan baik bahkan surat nikah dan surat cerai Bung Karno dengan Ibu Inggit
Garnasih di tahun 1942 masih ada dan turut dipamerkan, disini saya diajak
meresapi empat tahun hidup Bung Karno yang sunyi namun penuh visi.
Setelah berpamitan, saya dan mas Heru meninggalkan
Ende untuk melanjutkan perjalanan ke Boawae—75 km jauhnya. Di tengah ayunan
pedal, saya melihat sosok familiar, David! Si hitchhiker asal Kanada itu sedang
berjalan kaki, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat pertama kami bertemu
di Moni.
Kali ini giliran saya yang menegur, dia sempat
kaget dan akhirnya kita tertawa-tawa di pinggir jalan itu, berbincang tentang
makanan lokal dan sempat saya sarankan untuk mengunjungi rumah Bung Karno, ia
setuju lalu kami berpisah lagi.
Jalanan sepi membuat percakapan kami mengalir deras, Mas Heru asli Tulung Agung besar di Bali, menikah dengan perempuan Bima dan sudah berdinas di Ende selama 13 tahun. Seorang Bripka dengan dedikasi tinggi bertugas sebagai Babinkamtibmas di Desa Borokanda—searah jalan dengan saya yang menuju boawae.
Sebelum berpisah di tempat tugasnya, kami sempatkan foto
bareng. Sang fotografer dadakan: seorang anak SD yang baru pulang sekolah, detik
kecil yang akan terus saya ingat.
Jalur Trans Flores di pesisir Ende itu menyambut saya dengan terik matahari yang panasnya bisa menyentuh 35 derajat, hingga di beberapa titik harus berhenti, berteduh dan menyerap air.
Jalanan sebagian
sudah lebar, 7 meter sesuai standar nasional, sisanya masih sempit—mungkin
menunggu anggaran tambahan, seperti penjelasan petugas Binamarga di Talibura
beberapa hari lalu.
Merasa tubuh sedikit lemah saya mampir di sebuah
warung dan memesan segelas kopi, sang ibu pemilik kios itu bilang tidak menjual
kopi, namun tiba-tiba dari bangku di dekat situ seorang bapak tua berteriak ke
rumah sebelahnya, meminta dibuatkan kopi untuk saya. Ternyata suara itu datang
dari Pak Ahmad, tetua kampung disitu yang mana semua rumah di sekelilingnya
adalah anak-anaknya.
Dengan peci hitam dan batik rapi siap bepergian,
Pak Ahmad bercerita tentang anaknya yang berdinas sebagai TNI di Jayapura, pulang
mudik tiga tahun sekali, katanya. Setelah kopi hangat hadir dan berbagai cerita
mengalir, angkutan kota yang ia tunggupun datang. Ia pamit, meninggalkan jejak
hangat di perjalanan ini.
Melintasi Senyap Menuju Boawae: Kopi Kampung, Batu Berwarna dan Cahaya
di Tengah Gelap.
Segelas kopi hangat dari kebun miliknya sendiri
membuat tubuh saya kembali bertenaga, rasanya pekat dan bersahaja. Saat saya
bertanya soal harga, si ibu itu menolak halus, “Tamu Bapak tak usah bayar,”
ujarnya sambil tersenyum. Diam-diam saya selipkan selembar uang di bawah
piringnya—bukan semata untuk kopi, tapi sebagai penghormatan untuk tutur lembut
dan wejangan singkat dari seorang tua yang bijak.
Matahari masih menggigit, pohon kelapa di pinggir jalan sesekali jadi payung alami, di tengah lapar yang mulai mendera saya singgahi sebuah pondok makan di kawasan Batu Hijau, pantai yang tenang dan nyaman cocok untuk melepas penat.
Sepeda saya senderkan di gazebo dan nasi
bungkus pemberian Mas Heru jadi santapan saya siang itu ditemani jus nanas dan
semilir angin laut ende.
Pantai ini tak biasa. Batu-batu kecil
berwarna-warni berserakan, konon katanya berasal dari lava di bawah laut. Selain
daerah Batu Hijau ada juga Batu Biru—barisan pesisir yang menyimpan corak alam
tak terduga.
Di antara tamu yang datang saya sempat berbincang
dengan seorang manajer pemasaran produk minuman ternama. Ibunya asal Cianjur, iapun
memberikan referensi tempat menginap di Ruteng nanti—saya catat rapi di buku
kecil.
Saat perjalanan berlanjut ke Nangaroro, jalan
mulai menanjak, berkelok pelan. Kebun kelapa, kemiri, dan kakao mengisi
kiri-kanan jalan, penduduk tampak sibuk membersihkan ranting dan menyapa ramah
dari ladang mereka.
Tiba di mBay hari mulai redup, di persimpangan tiga saya ambil ke kiri menuju Boawae. Sisa jarak: 35 km. Saya siapkan lampu senter di atas stang karena malam mulai tiba, namun cahaya senter meredup ternyata baterenya nyaris habis—mungkin karena digunakan malam sebelumnya saat listrik PLN putus.
Saya cari warung berharap ada baterai baru, namun warung
sulit ditemukan.
Kondisi gelap sekali, beberapa penduduk berjalan pulang dari ladang tanpa cahaya. Ketika motor lain lewat saya coba lagi, motor itu akhirnya melambat dan menyapa ramah namun suara mereka terdengar khas, ternyata sepasang waria yang hendak pulang ke Boawae dan menyarankan saya untuk berhati-hati.
Gelap yang menyelimuti malam itu adalah pengalaman pertama saya mengayuh tanpa bintang, tanpa bulan, hanya ditemani suara binatang malam. Di kampung berikutnya barulah ketemu warung yang masih buka.
Saya berhenti tepat di bawah lampu penerangan yang terang benderang—beberapa
pemuda tengah nongkrong sambil menyeruput Moke. Untungnya barang yang dicari
tersedia, setelah dipasang cahaya senter kembali terang rasanya seperti
menemukan harapan.
Pemuda-pemuda di warung itu lalu memberi info bahwa Boawae sudah tak jauh lagi tapi pendakian pegunungan Abulobo setinggi 1.100 mdpl harus dilewati dulu. Tak ada pilihan saya mulai mendaki. Samar-samar pepohonan merayap di lerengnya, tanjakan curam sempat membuat nyali ciut tapi langkah tak boleh mundur.
Akhirnya, turunan panjang terbentang, walau gelap
masih pekat, jurang di kanan tak tampak jelas, saya kayuh perlahan namun mantap
hingga tibalah di sebuah rumah pertama dengan lampunya yang menggantung depan di
teras.
Saya berhenti sejenak, membakar sebatang rokok,
meresapi perjalanan. Sang pemilik rumah keluar dan menawarkan saya untuk masuk,
tapi saya sampaikan hanya sebentar saja untuk menyapa malam. Rokok
habis saya lanjutkan kayuhan, beberapa bukit terlalui hingga tibalah di lokasi penginapan
yang dituju—terletak di pertigaan Boawae menuju Pasarabu.
Sepeda saya parkirkan di garasi, pintu diketuk tapi tak ada jawaban, akhirnya datang seorang ibu muda yang indekos di sana yang baru pulang kerja di bank di seberang jalan. Ia pun memanggilkan sang pemilik penginapan.
Alhamdulillah kamarpun tersedia, saat lapar
menyerang saya menanyakan tempat warung makan. “Sudah tutup semua sekarang
sudah pukul 22,” kata ibu tadi. Mungkin karena iba ia minta pembantunya yang
sempat terjaga tadi untuk menyiapkan saya makan malam.
Sepiring nasi putih dan telur ceplok dadakan menjadi hidangan hangat yang penuh berkat dimalam itu.
 |
| Patung Bung Karno diabadikan di salah satu sudut taman perenungan di kota Ende. |
 |
| Sebagian barang-barang memorabilia BK disimpan di ruang belakang yang menghadap Taman. |
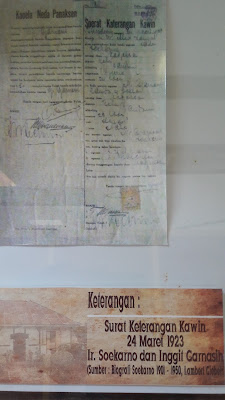 |
| No comment. |
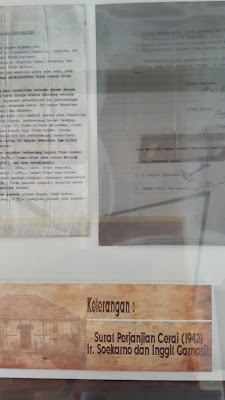 |
 |
| Polisi Asyik. |
 |
| Didepan kantor Babinkamtibmas Borokanda, diabadikan oleh pelajar SD yang baru pulang sekolah. |
 |
| Bersama Pak Ahmad yang hendak menuju Mbay. |
Melintasi Senyap Menuju Boawae: Kopi Kampung, Batu Berwarna, dan Cahaya di Tengah Gelap
Segelas kopi hangat dari kebun miliknya sendiri membuat tubuh saya kembali bertenaga. Rasanya pekat dan bersahaja. Saat saya bertanya soal harga, si ibu itu menolak halus, “Tamu Bapak tak usah bayar,” ujarnya sambil tersenyum. Diam-diam, saya selipkan selembar uang di bawah piringnya—bukan semata untuk kopi, tapi sebagai penghormatan untuk tutur lembut dan wejangan singkat dari seorang tua yang bijak.
Siang masih menggigit. Pohon kelapa di pinggir jalan sesekali jadi payung alami. Di tengah lapar yang mulai mendera, saya singgah di sebuah pondok makan di kawasan Batu Hijau, pantai yang tenang dan nyaman, cocok untuk melepas penat. Sepeda saya senderkan di gazebo, sementara nasi bungkus pemberian Mas Heru jadi santapan siang ditemani jus nanas dan semilir angin.
Pantai ini tak biasa. Batu-batu kecil berwarna-warni berserakan, konon katanya berasal dari lava di bawah laut. Selain daerah Batu Hijau, ada juga Batu Biru—barisan pesisir yang menyimpan corak alam tak terduga. Di antara tamu yang datang, saya sempat berbincang dengan seorang manajer pemasaran produk minuman ternama. Ibunya asli Cianjur. Ia memberi beberapa referensi tempat menginap di Ruteng nanti—saya catat rapi di buku kecil.
Perjalanan berlanjut ke Nangaroro. Jalan mulai menanjak, berkelok pelan. Kebun kelapa, kemiri, dan kakao mengisi kiri-kanan jalan. Penduduk tampak sibuk membersihkan ranting dan menyapa ramah dari ladang mereka.
Hari mulai redup ketika saya tiba di simpang tiga. Arah kanan ke Mbay, saya ambil kiri menuju Boawae. Sisa jarak: 35 km. Saya siapkan lampu senter di atas stang sepeda karena malam mulai tiba.
Cahaya senter meredup. Baterainya nyaris habis—mungkin karena digunakan malam sebelumnya saat listrik PLN putus. Saya cari warung, berharap bisa membeli baterai baru, tapi tak kunjung ditemukan.
Di tengah gelap, terdengar suara motor mendekat. Saya beri aba-aba, berharap ia mau menemani dengan sinar lampunya. Ternyata si pengendara—seorang PNS dengan seragam lengkap—juga tak punya lampu. Ia buru-buru mengejar waktu sebelum malam datang sepenuhnya.
Langit gelap betul. Beberapa penduduk berjalan pulang dari ladang tanpa cahaya. Ketika motor lain lewat, saya coba lagi menghentikan. Dua pengendara akhirnya melambat. Suara mereka khas. Ternyata sepasang waria yang hendak pulang ke Boawae. Dengan dandanan nyentrik dan suara yang jenaka, mereka menyapa ramah, lalu lanjut perjalanan setelah menyarankan saya untuk berhati-hati.
Gelap yang menyelimuti malam itu adalah pengalaman pertama saya mengayuh tanpa bintang, tanpa bulan, hanya ditemani suara binatang malam.
Di kampung berikutnya, barulah ketemu 2 warung yang masih buka. Saya berhenti di salah satu yang lengkap—beberapa pemuda nongkrong sambil menyeruput Moke. Untungnya barang yang dicari, baterai, tersedia. Setelah dipasang, cahaya senter kembali terang. Rasanya seperti menemukan harapan.
Pemuda2 warung itu lalu memberi info bahwa Boawae sudah tak jauh lagi. Tapi pendakian pegunungan Abulobo setinggi 1.100 mdpl harus dilewati dulu. Tak ada pilihan, saya mulai mendaki. Rimbun pepohonan merayap di lereng. Tanjakan curam sempat membuat nyali ciut, tapi langkah tak boleh mundur.
Akhirnya, turunan panjang terbentang. Gelap masih pekat, jurang di kanan tak tampak jelas. Saya kayuh perlahan namun mantap, hingga tibalah di sebuah rumah dengan lampu menggantung di teras.
Saya berhenti, membakar sebatang rokok, meresapi perjalanan. Sang pemilik rumah keluar, menawarkan saya masuk. Tapi saya sampaikan hanya ingin duduk sebentar saja dan menyapa malam. Sebatang habis, saya lanjutkan kayuhan. Bukit-bukit dilalui, hingga tibalah di lokasi penginapan yang dituju—terletak di pertigaan Boawae menuju Pasarabu.
Sepeda saya parkirkan di garasi. Saya ketuk pintu, tapi tak ada jawaban. Seorang ibu muda yang indekos di sana akhirnya datang, rupanya ia baru pulang kerja dari bank di seberang jalan. Ia pun memanggil sang pemilik penginapan.
Kamar tersedia. Pannier saya lepas dan dibawa masuk. Saat lapar menyerang, saya menanyakan tempat warung makan. “Sudah tutup semua, sekarang sudah pukul 22,” kata ibu tadi. Mungkin karena iba, ia minta pembantunya yang sempat terjaga, untuk membuatkan makan malam. Sepiring nasi putih dan telur ceplok dadakan—hidangan hangat yang terasa seperti berkat.
 |
| Resort makan Batu Hijau. |
 |
| Santai setelah mengisi perut. |
 |
| Jalanan mulus dan sepi. |
 |
| Bunga liar di Nangapanda |
 |
| Anak Toba di pertigaan menuju Mbay. |
Labels: bike to pulau, ende, soekarno, sukun



0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home